PLATFORM AGROEKOLOGI: RUMAH BESAR KEDAULATAN PANGAN KALIMANTAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PLATFORM AGROEKOLOGI: RUMAH BESAR KEDAULATAN PANGAN KALIMANTAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PLATFORM AGROEKOLOGI: RUMAH BESAR KEDAULATAN PANGAN KALIMANTAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PLATFORM AGROEKOLOGI: RUMAH BESAR KEDAULATAN PANGAN KALIMANTAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PLATFORM AGROEKOLOGI: RUMAH BESAR KEDAULATAN PANGAN KALIMANTAN
Oleh Sani Lake
Kalimantan hari ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, hutan, tanah, dan airnya menyimpan sumber kehidupan yang tak ternilai. Di sisi lain, gempuran tambang batubara, perkebunan sawit, food estate, dan proyek ekstraktif telah menekan ruang hidup masyarakat adat dan petani. Dalam situasi krisis iklim dan krisis pangan global, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana rakyat Kalimantan dapat mempertahankan haknya atas pangan sehat, tanah, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan?
Jawabannya bisa kita temukan dalam satu konsep penting: Platform Agroekologi. Agroekologi bukan sekadar cara bertani organik, tetapi sebuah jalan perubahan sistem yang menyatukan produksi, distribusi, konsumsi, hingga kebijakan. Profesor Miguel Altieri, pionir agroekologi, menegaskan bahwa agroekologi adalah ilmu, praktik, dan gerakan sosial yang membebaskan petani dari ketergantungan korporasi. Di Kalimantan, ini menjadi sangat relevan karena tanah dan hutan adalah basis kehidupan orang Dayak.
Apa Itu Platform Agroekologi?
Platform agroekologi dapat dipahami sebagai rumah besar tempat semua unsur perjuangan pangan bertemu. Ia adalah kerangka ideologi, ruang jaringan, wadah praktik, sekaligus instrumen advokasi. Menurut Vandana Shiva, aktivis lingkungan dari India, tanpa sebuah platform kolektif, praktek pertanian sehat akan mudah diserap pasar dan kehilangan makna politiknya. Platform inilah yang menjadi kompas moral dan sekaligus payung gerakan.
Empat elemen inti platform adalah: 1) Nilai : keberagaman, keadilan sosial, kemandirian komunitas, kesehatan ekosistem. 2) Praktik : sekolah tani, bank benih, demplot agroekologi, pasar rakyat. 3) Jaringan : forum komunitas, koalisi organisasi masyarakat sipil, akademisi, konsumen. 4) Advokasi : mengubah kebijakan publik agar berpihak pada petani dan masyarakat adat.
Pilar-Pilar Platform Agroekologi
Sebuah platform agroekologi idealnya dibangun di atas enam pilar: prinsip dasar, ruang belajar, infrastruktur pangan, advokasi kebijakan, ekonomi alternatif, dan koneksi global. Seperti diingatkan Ibu Maria Ulfah, praktisi pertanian organik di Kalimantan Tengah, tanpa pilar pasar lokal yang adil, petani tidak akan termotivasi melestarikan benih lokalnya. Sedangkan menurut Jose Graziano da Silva, mantan Direktur FAO, agroekologi adalah jalan utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Konteks Kalimantan: Tantangan dan Peluang
Kalimantan menghadapi krisis lingkungan (deforestasi, tambang, food estate, kebakaran gambut), ancaman pangan lokal (GMO, pupuk kimia), konflik agraria, dan lemahnya perlindungan tanah adat. Namun modal sosial Dayak, - pengetahuan rotasi ladang, ritual pangan, dan solidaritas adat - masih kuat. Seperti diungkapkan Tjilik Riwut dalam catatannya, tanah dan hutan adalah 'ibu' yang memberi kehidupan. Maka menjaga pangan lokal berarti menjaga martabat orang Dayak itu sendiri.
Wujud Konkret Platform di Kalimantan
Di level lokal ada bank benih padi gunung di Barito Timur, sekolah tani Dayak Ngaju di Katingan, festival pangan lokal tiap tahun. Lalu pada level provinsi terdapat Forum Agroekologi Kalimantan, pusat belajar agroekologi, koperasi CSA. Dan di level nasional/regional ada jaringan agroekologi Asia seperti APEX (Asian People Exchange), jaringan belajar IPEX (Indonesian People Exchange), advokasi kebijakan pangan nasional, partisipasi di COP30. Dr. Marko Mahin, peneliti Dayak Ma’anyan, menekankan pentingnya pengakuan pemerintah daerah atas praktik ini, karena tanpa legitimasi kebijakan, praktek komunitas rentan dimarginalkan.
Mengapa Publik Harus Peduli?
Agroekologi bukan hanya urusan petani, tetapi urusan semua orang yang makan. Di kota Palangka Raya, Banjarmasin, hingga Jakarta, masyarakat menginginkan pangan sehat, aman, dan terjangkau. Dengan mendukung agroekologi, masyarakat kota ikut melawan monopoli pangan korporasi besar. Seperti dikatakan Ernesto Bebbington, pakar pembangunan berkelanjutan, agroekologi adalah jembatan antara desa dan kota yang memperkuat solidaritas sosial. Publik yang peduli dapat berkontribusi dengan membeli produk lokal, mendukung CSA, atau mendorong kebijakan daerah.
Pada akhirnya, platform agroekologi adalah rumah besar yang menyatukan gerakan sosial, budaya, ekonomi alternatif, dan politik pangan. Di Kalimantan, platform ini adalah jawaban atas krisis tanah, hutan, dan pangan. Lebih dari itu, platform ini adalah jalan pulang, sebuah upaya kembali pada pengetahuan leluhur, tanah yang subur, dan solidaritas antar komunitas. Seperti ungkapan Dayak: 'Tanah adalah ibu, benih adalah anak, pangan adalah kehidupan.' Melalui platform agroekologi, Kalimantan menjaga ibu bumi, merawat anak-anak benih, dan memastikan kehidupan berlanjut adil dan berkelanjutan.
Catatan Kaki & Referensi
1. Miguel Altieri (2018). Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. CRC Press.
2. Vandana Shiva (2016). Who Really Feeds the World? The Failures of Agribusiness and the Promise of Agroecology. North Atlantic Books.
3. Maria Ulfah – Praktisi pertanian organik Kalimantan Tengah, wawancara komunitas (2023).
4. Jose Graziano da Silva (2019). FAO and Agroecology: A Pathway to Achieve the SDGs. FAO Publications.
5. Tjilik Riwut (1958). Kalimantan Membangun. Jakarta: PN Balai Pustaka.
6. Marko Mahin (2021). Penelitian Dayak Ma’anyan dan Sistem Pangan Lokal. Laporan Penelitian, Universitas Palangka Raya.
7. Ernesto Bebbington (2020). Sustaining the Andes: Agroecology, Livelihoods and Development. Routledge.

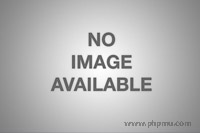 Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini