RESENSI BUKU: KODRAT ALAM – VANDANA SHIVA
Klik Untuk Lebih Jelas : RESENSI BUKU: KODRAT ALAM – VANDANA SHIVA
Klik Untuk Lebih Jelas : RESENSI BUKU: KODRAT ALAM – VANDANA SHIVA
Klik Untuk Lebih Jelas : RESENSI BUKU: KODRAT ALAM – VANDANA SHIVA
Klik Untuk Lebih Jelas : RESENSI BUKU: KODRAT ALAM – VANDANA SHIVA
By Kirana Esel
Di tengah gelombang krisis iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan kerentanan pangan global, Vandana Shiva kembali menegaskan suaranya melalui buku "Kodrat Alam". Sebagai fisikawan, filsuf, sekaligus aktivis ekofeminis, Shiva membongkar akar persoalan ekologi kontemporer: bukan manusia secara umum yang menjadi biang kerusakan, melainkan segelintir korporasi global dan miliarder yang mengendalikan teknologi, energi, serta pangan dunia [1].
Shiva memperkenalkan istilah gangguan metabolik perubahan iklim. Krisis iklim baginya bukan sekadar fenomena alamiah, melainkan hasil dari proses “metabolisme sosial” manusia modern yang memutuskan relasi timbal balik dengan bumi. Ketika kapitalisme global mengekstraksi sumber daya tanpa batas, tanah kehilangan kesuburan, benih kehilangan keragaman, dan manusia kehilangan kedaulatannya atas pangan. Dalam bahasa Shiva, kodrat alam dilanggar, dan akibatnya adalah krisis multidimensi: iklim, kesehatan, hingga pangan [2].
Shiva menolak istilah antroposen yang populer di kalangan ilmuwan Barat. Menurutnya, istilah ini menyalahkan seluruh umat manusia sebagai penyebab, padahal kenyataannya, masyarakat adat dan komunitas lokal sering menjadi korban pertama sekaligus benteng terakhir dari krisis ekologi. Penyebab utamanya adalah kapitalosentrisme—sistem ekonomi yang menempatkan korporasi besar sebagai pusat pengelolaan alam [3].
Salah satu kekuatan buku ini terletak pada sudut pandang ekofeminis. Shiva menyoroti bagaimana perempuan menjadi pihak paling terdampak kerusakan alam: dari gagal panen, krisis air, hingga hilangnya benih lokal. Namun, perempuan juga diposisikan sebagai aktor utama dalam menjaga kehidupan. Melalui pengalaman sehari-hari sebagai petani, pengumpul benih, dan pengelola pangan keluarga, perempuan memelihara keragaman hayati dan memastikan keberlanjutan komunitas [4].
Perspektif ini penting dibaca dalam konteks Indonesia. Masyarakat adat Dayak, misalnya, memiliki tradisi kuat dalam pengelolaan ladang, hutan, dan sungai. Perempuan Dayak berperan menjaga benih padi, umbi, sayuran, dan obat-obatan lokal. Namun, mereka pula yang pertama kali menanggung akibat ketika hutan digunduli untuk sawit atau tambang batu bara. Pesan Shiva menjadi gema global bagi perjuangan lokal: menjaga pangan berarti menjaga hidup.
Buku ini adalah kritik tajam terhadap kapitalisme neoliberal. Shiva menelusuri bagaimana korporasi benih dan agrokimia—seperti Monsanto, Bayer, dan Syngenta—memonopoli kehidupan melalui paten, GMO, dan pestisida kimia. Ia menegaskan bahwa model pembangunan yang bergantung pada industri pangan global bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga memperdalam ketidakadilan sosial: petani kecil kehilangan kedaulatan, sementara segelintir orang menguasai rantai nilai pangan [5].
Shiva juga mengaitkan krisis iklim dengan krisis demokrasi. Menurutnya, ketika keputusan politik tunduk pada kepentingan korporasi, rakyat kehilangan kendali atas masa depan ekologinya. Inilah yang ia sebut sebagai kolonialisme baru atas alam.
Meski sarat kritik, Kodrat Alam bukanlah buku pesimistik. Shiva menawarkan “jalan pulang”: kembali ke kedaulatan pangan, agroekologi, dan solidaritas komunitas. Ia mengutip banyak contoh gerakan rakyat—dari petani India yang menolak GMO, komunitas Amerika Latin yang mempertahankan benih asli, hingga gerakan lokal di Afrika dan Asia yang memperjuangkan agroekologi [6].
Jalan ini tidak hanya teknis, tapi juga filosofis. Agroekologi bukan sekadar metode bertani ramah lingkungan, melainkan praktik politik untuk mengembalikan kendali kepada rakyat. Dengan menghormati kodrat alam, manusia bisa membangun relasi yang adil, setara, dan berkelanjutan dengan bumi.
Kodrat Alam adalah bacaan penting bagi siapa saja yang peduli pada masa depan bumi. Gaya tulisannya menggabungkan kedalaman teori dengan kisah-kisah nyata dari lapangan, menjadikannya relevan baik untuk akademisi, aktivis, maupun masyarakat umum. Di Indonesia, di mana deforestasi, tambang, dan perkebunan sawit mengancam pangan lokal, pesan buku ini sangat kontekstual: tanpa kedaulatan pangan, kita kehilangan kedaulatan hidup.
Buku ini bukan sekadar kritik, tapi juga undangan untuk bergerak. Ia mengingatkan bahwa solusi krisis iklim tidak datang dari teknologi mahal atau kebijakan top-down, melainkan dari keberanian komunitas menjaga benih, tanah, dan alamnya sendiri.
Catatan
[1] Vandana Shiva, Kodrat Alam: Gangguan Metabolik Perubahan Iklim (Marjin Kiri, 2023), hlm. 15–20.
[2] Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (London: Verso, 2016).
[3] Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life (London: Verso, 2015).
[4] Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology and Development (London: Zed Books, 1989).
[5] Philip McMichael, Development and Social Change (Los Angeles: Sage, 2017).
[6] Vandana Shiva, Soil Not Oil: Environmental Justice in an Age of Climate Crisis (Cambridge, MA: South End Press, 2008).

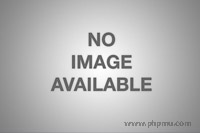 Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini