Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Klik Untuk Lebih Jelas : Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Klik Untuk Lebih Jelas : Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Klik Untuk Lebih Jelas : Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Klik Untuk Lebih Jelas : Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Alam sebagai Rumah Bersama
Di Kalimantan, cara pandang Dayak terhadap alam - hutan, sungai, tanah, langit - bukan sekadar ekologi, melainkan ontologi: alam adalah rumah kosmis tempat manusia, leluhur, dan Sang Pencipta saling berelasi. Di tengah krisis iklim dan erosi keanekaragaman hayati global, cara pandang ini relevan karena menempatkan alam sebagai subjek moral - bukan objek eksploitasi. Lintasan sejarah kolonialisme, konsesi kayu dan tambang, ekspansi sawit, serta proyek infrastruktur modern telah mengubah intensitas relasi ini - dari harmoni menuju tekanan dan konflik - namun juga memantik kebangkitan gerakan adat untuk pemulihan dan pembaruan tata kelola. Bukti empiris global pun kian mengakui peran krusial pengetahuan adat dan komunitas lokal dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan - itu ditegaskan IPBES (panel sains-kebijakan PBB untuk keanekaragaman hayati).
Kosmologi Dayak: Ranying Hatalla, Belom Bahadat, dan simbol kosmis
Banyak komunitas Dayak (mis. Ngaju) mengenal Ranying Hatalla Langit sebagai Yang Ilahi, dengan teks Panaturan yang mengajarkan keterhubungan jagat raya; agama lokal Kaharingan memperoleh pengakuan lebih kokoh sejak Indonesia mengakui aliran kepercayaan pada 2017 (sebelumnya sering “diindukkan” ke Hindu untuk alasan administratif).
Nilai etik Belom Bahadat - kira-kira “hidup beradat/bermoral” - menjadi prinsip hidup dan hukum adat Ngaju; ia ditautkan dalam memori kolektif hingga perjanjian damai Tumbang Anoi (1894) dan terus dipakai sebagai etos ketertiban sosial-ekologis.
Simbol Batang Garing (Pohon Kehidupan) mengikat kosmologi ruang: sumbu vertikal (langit-bumi) dan cabang yang menyimbolkan keseimbangan, kerap menjadi rujukan dalam tata ruang rumah betang dan halaman upacara.
Ritual-ritual menjaga keterhubungan manusia-alam-leluhur: Tiwah (Ngaju) mengantar roh menuju “lewu tatau” (alam baka) seraya meneguhkan tatanan kosmos; Manajah Antang memohon petunjuk arah atau keputusan, menandai bagaimana “tanda alam” dibaca sebagai bahasa moral.
Alam dalam Praktik Kehidupan: dari ladang berpindah, hukum adat, hingga arsitektur
Ladang berpindah (swidden atau shifting cultivation) Dayak adalah agroekosistem rotasional: membuka lahan secukupnya, menanam (sering padi ladang), lalu membiarkan tanah beristirahat dalam masa bera agar pulih (7–15 tahun bervariasi lokal). Jika dikelola baik (rotasi cukup, pengendalian api, mosaik lanskap), riset CIFOR/ICRAF dan kajian kawasan Borneo menunjukkan swidden dapat mempertahankan jasa ekosistem, meminimalkan erosi setelah fase awal, dan menjaga mozaik keanekaragaman hayati lebih baik daripada monokultur permanen.
Hukum adat mengatur zonasi: hutan keramat (tak boleh ditebang), sempadan riparian (larangan mencemari), larangan menebang jenis pohon tertentu, serta tata denda yang memulihkan relasi sosial-ekologis - sebuah “konstitusi ekologis” berbasis komunitas. Di ranah hunian, rumah betang (rumah panjang) memadukan fungsi sosial, ritual, dan ekologis: struktur panggung mengantisipasi banjir, sirkulasi udara, dan ruang komunal sebagai sekolah nilai hidup (musyawarah, gotong-royong, pendidikan adat).
Pengetahuan pangan-obat tradisional (etnobotani) terikat siklus hutan: rotasi kebun, kebun hutan (dengan karet, buah, rempah), serta zona hutan sekunder/primer membentuk mosaik pasokan hidup; sejumlah studi di Borneo memperlihatkan keanekaragaman pohon dan jasa ekosistem tertinggi di hutan alami, tetapi transisi swidden - kebun hutan menjaga bagian penting dari fungsi ekologis.
Perubahan dan Tantangan: kolonial, Orde Baru, ekstraktivisme baru
Sejak kolonialisme, hutan Kalimantan ditata sebagai komoditas (kayu/logging), dengan hukum kolonial menempatkan hutan berada di bawah otoritas negara - menyisihkan kedaulatan hukum adat atas ruang hidup. Pada Orde Baru, HPH(konsesi kayu), perkebunan sawit, tambang, dan transmigrasi mengubah skala bentang alam. Era kontemporer menambahkan nikel (untuk baterai EV), smelter, dan proyek infrastruktur besar; 2023 tercatat kenaikan kehilangan hutan primer Indonesia (analisis WRI) meski tren jangka panjang menurun dibanding puncak 2010-an.
Data Global Forest Watch memperlihatkan Indonesia masih kehilangan hutan alam dalam skala signifikan; dasbor terbaru mencatat kehilangan 259 ribu ha hutan alam pada 2024 (estimasi GFW), dengan proporsi kehilangan hutan alam di provinsi Kalimantan Timur 2021-2024 mencapai 67% dari total hilang tutupan pohon (Kaltim), dan 39% di Kalimantan Selatan. Angka-angka ini menandakan tekanan yang belum selesai, meski kebijakan moratorium sawit dan pencegahan kebakaran memperbaiki tren kebakaran besar.
Dinamika IKN (Ibu Kota Nusantara) menambah layer baru: kajian akademik 2003-2023 menunjukkan lonjakan area terbangun, penurunan lahan pertanian, dampak pada keanekaragaman hayati, pangan, dan penghidupan komunitas pedesaan/adat (Paser, Kutai, Balik, Dayak). Potensi konflik tenurial, peminggiran budaya, dan perubahan sistem mata pencaharian menjadi sorotan yang memerlukan guardrail sosial-lingkungan kuat (KLHS, FPIC, pengakuan hutan adat).
Di sisi kultural, Kaharingan mengalami tekanan historis (pengindukan ke Hindu demi pengakuan administratif) dan baru memperoleh penguatan pengakuan sebagai aliran kepercayaan pasca putusan MK 2017 - menunjukkan bagaimana politik pengakuan memengaruhi ekologi iman dan relasi masyarakat-alam.
Resistensi dan Kebangkitan: MK35/2012, AMAN, FPIC, inovasi komunitas
Tonggak hukum penting: Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan melekat pada wilayah adat masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat dasar klaim, restorasi wilayah, dan tata kelola berbasis adat—meski implementasinya bertahap dan bergantung pengakuan MHA oleh daerah.
Gerakan AMAN dan jejaring adat Dayak (mis. Gerdayak) mendorong pemetaan partisipatif, pengakuan MHA, hutan desa, community forestry, dan bank benih lokal. Dalam kemitraan, prinsip FPIC/PADIATAPA wajib: persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan - hak kolektif Masyarakat Adat untuk memberi/menolak persetujuan atas proyek yang berdampak pada wilayah mereka. Panduan UN-REDD, OHCHR, RSPO, dan kerangka akuntabilitas sektor swasta menekankan inklusivitas (perempuan, pemuda), transparansi informasi, dan konsultasi bermakna.
Di akar rumput, banyak komunitas Dayak mengembangkan sekolah lapang agroekologi, kebun hutan multistrata (karet, buah, kopi/kakao, rotan), dan penguatan pasar lokal adil - merawat landasan kosmologis sambil menambah ketahanan ekonomi keluarga. Bukti komparatif di Asia Tenggara menunjukkan sistem swidden berbera panjang dapat lebih baik mempertahankan jasa ekosistem dibanding sejumlah bentuk penggunaan lahan alternatif bila syarat-syarat ekologis dan sosial terpenuhi.
Dayak dalam Lintasan Global: menghindari mitos, memperkuat bukti
Narasi global kerap menyitir klaim berlebih (mis. “Masyarakat Adat melindungi 80% biodiversitas dunia”). Kajian jurnalisme sains menunjukkan angka 80% itu tidak berbasis data - dan justru dapat merusak kredibilitas advokasi adat. Yang akurat adalah keterlibatan bermakna Masyarakat Adat - hak, pengetahuan, dan tata Kelola - memperkuat konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, sebagaimana rangkaian penilaian IPBES dan kebijakan FAO tentang peran pengetahuan adat dalam sistem pangan dan agroekologi.
Kerangka agroekologi (Koalisi Agroekologi, GIZ/WWF dkk.) mengaitkan pengetahuan adat dengan solusi keanekaragaman hayati-pangan-iklim; laporan kebijakan 2025 menandai pengakuan agroekologi dalam proses CBD (COP12/13) dan menempatkan pengetahuan/praktik komunitas sebagai pilar transformasi sistem pangan.
Dalam horizon etika global, cara pandang Dayak selaras dengan ekologi mendalam: alam sebagai subjek moral; manusia bagian, bukan pusat. Ini bukan romantisasi, melainkan pilihan rasional berbasis pengalaman panjang mengelola ketidakpastian ekologis melalui rotasi lahan, larangan adat, dan ritus yang “mengikat” perilaku dengan konsekuensi sosial-spiritual.
Implikasi Praktis: dari teori ke kebijakan - apa yang perlu dilakukan?
Pengakuan & Implementasi Hukum: percepat pengakuan MHA oleh pemda (prasyarat kuat implementasi MK35), sertifikat sosial untuk hutan adat, conflict resolution berbasis adat-negara.
FPIC sebagai “rem sabuk pengaman”: jadikan FPIC syarat mutlak di semua proyek ekstraktif/infrastruktur di wilayah adat (termasuk IKN dan rantai pasok sawit/nickel), dengan monitoring independen dan sanksi jika dilanggar.
Ekonomi Adil & Agroekologi: dukung kebun hutan multistrata, bank benih lokal, pasar adil; batasi praktik yang memutus rotasi bera; pakai bukti CIFOR/ICRAF sebagai dasar desain program.
Pendidikan Kontekstual: integrasikan kosmologi, hukum adat, dan sains ekologi dalam kurikulum komunitas (betang sebagai ruang belajar), memperkuat generasi muda agar “melek adat-iklim-pasar” sekaligus.
Data Terbuka & Akuntabilitas: pakai near-real time data deforestasi (GFW), audit sosial lingkungan partisipatif, dan laporan berkala bentang alam Kalimantan sebagai basis negosiasi kebijakan.
Dari Hutan Adat ke Masa Depan Planet
Cara pandang Dayak menghadirkan tiga pelajaran universal. Pertama, alam bukan sumber daya “netral”, melainkan ruang relasi yang harus dijaga melalui etika (Belom Bahadat), ritus, dan aturan komunitas. Kedua, keberlanjutan bukan sekadar teknologi; ia politik pengakuan - atas tanah, iman/laku, dan cara tahu - yang dibuktikan oleh MK35 dan FPIC. Ketiga, masa depan sistem pangan-iklim membutuhkan hibridisasi pengetahuan: menggabungkan sains ekologi dan kebijaksanaan swidden berbera panjang, kebun hutan, dan tata kelola adat.
Dengan itu, “pandangan Dayak tentang alam” bukan romantika masa lalu, melainkan arsitektur moral-institusional untuk masa depan: bumi yang layak huni, adil, dan beragam, dari hutan adat Kalimantan untuk dunia.
*Sani Lake dari berbagai
Sumber Pustaka
- AMAN. (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Dokumen advokasi pengakuan hutan adat.
- Colfer, Carol J. Pierce. (2003). The Equitable Forest: Diversity, Community and Resource Management. Washington: RFF Press.
- Dove, Michael R. (1983). Theories of Swidden Agriculture and the Political Economy of Ignorance. Agroforestry Systems 1(2): 85–99.
- Global Forest Watch. (2024). Indonesia Primary Forest Loss Data. Washington DC: World Resources Institute.
- IPBES. (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
- King, Victor T. (1978). Essays on Borneo Societies. Oxford: Oxford University Press.
- Koalisi Agroekologi. (2025). Policy Brief on Agroecology. Jakarta: Koalisi Agroekologi.
- Mahin, Marko. (2005). Identitas Dayak dan Politik Lingkungan. Jurnal Antropologi Indonesia 29(3).
- Mihing, Yohanes. (2004). Agama Kaharingan: Sistem Kepercayaan dan Ritual Dayak Ngaju. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mongabay. (2021). Indigenous Peoples and Biodiversity: Debunking the 80% Myth. Artikel daring.
- Moniaga, Sandra. (1999). Hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Jurnal Hukum Lingkungan.

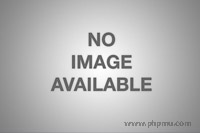 Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini