PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN
Klik Untuk Lebih Jelas : PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN
Petani adalah tulang punggung bangsa. Petani menanam padi, jagung, sayur, buah, kopi, dan kakao. Petani memberi makan keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun petani justru hidup dalam kerentanan di kampung-kampung. Krisis iklim mengubah musim dan pola tanam petani. Kebijakan impor mengubah harga dan psikologi pasar di desa. Kelaparan mengintai keluarga miskin pedesaan dan pinggiran kota. Petani berdiri di tengah badai yang datang dari banyak arah. Badai itu bukan hanya cuaca. Badai itu juga kebijakan, pasar, dan struktur ekonomi yang timpang. Hari Tani Nasional mengajak kita melihat akar masalah, bukan sekadar gejala. Kita perlu menggeser cara pandang dari sekadar produksi ke keadilan pangan. Kita perlu menempatkan petani sebagai subjek pembangunan, bukan objek bantuan.
Krisis Iklim Menghantam Sawah dan Ladang
Musim tidak menentu setiap tahun. Hujan datang terlambat dan berhenti mendadak. Kemarau datang terlalu panjang dan menyengat. BMKG mencatat 60% wilayah Indonesia mengalami perubahan pola hujan signifikan [1]. Data ini bukan angka kosong. Data ini menyatu dengan cerita petani. Di Indramayu, hujan menenggelamkan persemaian. Bibit padi membusuk di dalam lumpur. Petani mengulang proses dari nol. Di NTT, matahari membakar ladang jagung. Tunas menguning sebelum tumbuh. Di Flores, kopi rontok sebelum matang. Bunga gugur, buah mengecil. Di Kalimantan, banjir datang tiap tahun. Air merendam padi ladang. Ketika kemarau tiba, lahan gambut terbakar. Asap menutup langit berhari-hari. Petani kehilangan kalender tanam yang diwariskan leluhur. Pengetahuan lokal tentang bintang dan angin menjadi kurang akurat. Biaya produksi meningkat karena gagal tanam berulang. Petani membeli benih ulang. Petani membeli pupuk ulang. Petani berhutang ulang. Satu musim gagal panen berarti hutang menumpuk di koperasi. Satu musim gagal panen berarti dapur tidak mengepul di malam hari. Satu musim gagal panen berarti anak tidak berangkat sekolah. Krisis iklim juga membawa hama baru dan penyakit tanaman. Wereng, ulat grayak, dan tikus menyerang di luar pola lama. Petani bingung menentukan obat dan dosis yang aman. Beban kesehatan meningkat ketika petani menyemprot lebih sering. Tanah lelah karena pupuk kimia dipakai berlebih untuk mengejar panen. Air irigasi menurun volumenya. Sumur sawah mengering lebih cepat. Krisis iklim memukul tiga hal sekaligus: produksi, pendapatan, dan kesehatan petani.
Impor Pangan Menekan Petani
Pemerintah memilih jalan cepat untuk menutup defisit. Jalan cepat itu adalah impor pangan dalam jumlah besar. Beras, gula, kedelai, dan bawang putih masuk melalui pelabuhan [2]. Impor menenangkan pasar di kota, tetapi menekan harga di desa. Harga gabah lokal jatuh di bawah biaya produksi. Petani menjual dengan rugi karena panen tidak bisa disimpan lama. Bulog tidak selalu hadir tepat waktu di desa. Rantai pasok dikuasai segelintir pedagang besar. Impor tidak netral. Impor membentuk harapan konsumen pada harga murah. Harapan itu berbalik menjadi tekanan bagi produsen kecil. Impor juga menentukan varietas yang beredar dan selera makan di kota. Ketika impor murah masuk, lahan pangan lokal beralih fungsi. Keluarga muda meninggalkan sawah karena margin terlalu tipis. Soekarno mengingatkan bahwa urusan pangan adalah urusan hidup mati bangsa. Ketika bangsa bergantung pada impor, kedaulatan pangan runtuh. Ketika kurs bergejolak dan pasokan terganggu, harga di kota melonjak. Saat itu, beban justru kembali ke petani untuk meningkatkan produksi secara mendadak. Namun petani tidak bisa menambah produksi tanpa modal, benih, dan air.
Ancaman Kelaparan di Negeri Subur
Indonesia memiliki tanah luas dan air berlimpah. Namun kelaparan tetap muncul di banyak tempat. Kelaparan tidak selalu tampak di jalan kota. Kelaparan bersembunyi di rumah kayu dan barak pekerja harian. Stunting menjadi penanda kelaparan laten di keluarga miskin. Kemenkes (2022) mencatat prevalensi stunting nasional 21,6% [3]. Angka itu bukan statistik semata. Angka itu adalah wajah anak-anak desa. Banyak anak petani makan karbohidrat tanpa protein memadai. Sayur tidak selalu hadir di piring, meski tumbuh di kebun tetangga. Harga telur naik. Daging terlalu mahal. Ikan tidak selalu tersedia. Ibu-ibu mengatur uang belanja sambil menahan keinginan anak. Kelaparan juga berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi. Penyakit infeksi berulang menurunkan penyerapan gizi. Kelaparan bukan hanya ketiadaan pangan. Kelaparan adalah ketiadaan akses dan kuasa. Keadilan pangan menuntut distribusi yang merata dan harga yang adil.
Petani Terkepung Benih dan Pupuk
Petani tidak lagi bebas memilih benih dari lumbung sendiri. Benih lokal menipis karena digantikan benih hibrida yang dipatenkan. Benih hibrida dijual dalam kemasan cantik dengan harga tinggi. Petani membeli karena tergoda janji hasil tinggi. Namun benih hibrida sering butuh pupuk dan pestisida lebih banyak. Harga pupuk naik setiap musim. Pupuk bersubsidi langka di kios. Petani antre panjang, tetapi stok tidak selalu cukup. Pilihan terakhir adalah membeli pupuk nonsubsidi yang mahal. Ketergantungan menciptakan lingkaran hutang yang makin ketat. Sajogyo Institute mencatat 60% petani gurem berhutang setiap musim tanam [4]. Hutang membuat petani tidak leluasa menentukan waktu jual panen. Tengkulak menjemput gabah di sawah dengan harga ditentukan sepihak. Vandana Shiva mengingatkan bahaya monopoli benih bagi kehidupan petani. Ketika benih dimonopoli, kebebasan bermetamorfosis menjadi kontrak jangka panjang. Bank benih desa perlu dipulihkan agar petani bisa menyimpan dan menukar benih. Sekolah lapang agroekologi perlu mengajarkan perbanyakan benih lokal. Kemandirian benih akan mengurangi biaya dan menguatkan identitas pangan lokal.
Wajah Lapar Sang Penanam
Mari menatap wajah petani kecil di ujung desa. Petani menjual gabah Rp5.000 per kilo. Beras di kota Rp15.000 per kilo. Selisih harga tersapu oleh biaya penggilingan, transportasi, dan margin pedagang. Perempuan tani memikul beban ganda di ladang dan di rumah. Ia menanam, menyiangi, memanen, dan tetap memasak untuk keluarga. Ia menutup kekurangan gizi dengan mie instan dan teh manis. Ia menahan diri membeli lauk karena uang hanya cukup untuk beras. Anak-anak makan nasi lebih banyak untuk menahan lapar. Kemenkes mencatat stunting 21,6% pada 2022 [3]. Stunting mengurangi potensi kecerdasan dan produktivitas saat dewasa. Gus Dur mengingatkan penghormatan kita pada petani sebagai penopang bangsa. Kutipan itu menuntut tindakan nyata, bukan hanya tepuk tangan saat panen raya.
Siapa yang Kenyang?
Pertanyaan ini sederhana tetapi tajam: siapa yang kenyang? Importir pangan kenyang karena menguasai volume dan logistik. Korporasi benih dan pupuk kenyang karena memegang paten dan jaringan distribusi. Spekulan pasar kenyang karena bermain di gudang dan waktu rilis stok. Elit politik kenyang karena menjadikan pangan sebagai panggung kampanye. Sementara petani tetap lapar dan berada di barisan paling bawah rantai nilai. Ketimpangan ini tidak terjadi begitu saja. Ketimpangan ini hasil desain kebijakan. Subsidi banyak mengalir ke input, bukan ke kemandirian petani. Investasi banyak masuk ke hilir, bukan ke penguatan produsen kecil di hulu.
Jalan Keluar dari Badai
Kritik perlu diikuti tawaran jalan keluar yang konkret. Kedaulatan pangan harus menjadi arah kebijakan, bukan jargon musiman. Kedaulatan pangan berarti petani menentukan benih, lahan, dan pasar mereka sendiri. Negara menjamin akses tanah melalui reforma agraria yang nyata. Negara memperbaiki harga dasar gabah yang melindungi biaya dan marjin hidup layak. Agroekologi menjadi strategi adaptasi iklim sekaligus strategi kesehatan publik. FAO (2021) menegaskan potensi agroekologi untuk ketahanan sistem pangan [5]. Sekolah lapang perlu mengajarkan pembuatan kompos, pestisida nabati, dan konservasi air. Diversifikasi tanaman meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko gagal panen. Benih lokal harus dipulihkan melalui bank benih komunitas dan kebun plasma nutfah. Pemerintah daerah bisa menerbitkan peraturan perlindungan benih lokal. Koperasi petani memotong rantai tengkulak dan memperkuat posisi tawar. Platform digital desa-kota menghubungkan konsumen dengan petani secara langsung. Program pengadaan pemerintah harus menyerap produk petani kecil dengan harga adil. Politik pro-petani berarti anggaran berpihak pada layanan penyuluhan dan riset publik. KPA mencatat 212 konflik agraria pada 2022 [6]. Angka itu menuntut penyelesaian struktural. Tanah konflik harus dipulihkan untuk produksi pangan rakyat.
Harapan dari Tanah
Cuba bertahan dari krisis dengan agroekologi massal di kota dan desa. Kebun-kebun kota mengembalikan jarak pendek dari lahan ke meja makan. Bhutan memilih jalur pertanian organik yang memuliakan alam dan manusia. Indonesia bisa belajar tanpa menyalin mentah-mentah. Indonesia punya keunggulan keanekaragaman hayati dan budaya pangan. Gerakan pangan lokal bisa memperkuat kebanggaan pada beras lokal, jagung lokal, dan umbi lokal. Sekolah, puskesmas, dan dapur umum bisa menjadi pasar pasti bagi produk petani. Harapan lahir ketika kebijakan bertemu gerakan rakyat dan dukungan konsumen.
Petani berdiri di tengah badai iklim, impor, dan kelaparan. Badai ini bukan takdir. Badai ini bisa kita redam dengan pilihan kebijakan. Bangsa perlu memilih berpihak pada petani dan pangan lokal. Hari Tani Nasional bukan seremoni. Hari Tani Nasional adalah ajakan bertindak. Jika petani berdaulat, bangsa ikut berdaulat. Jika petani kenyang, rakyat ikut kenyang.
*Sani Lake
Referensi
[1] BMKG. (2023). Laporan Perubahan Iklim Indonesia.
[2] FAO. (2022). Food Outlook and Trade Statistics.
[3] Kementerian Kesehatan RI. (2022). Data Stunting Nasional.
[4] Sajogyo Institute. (2022). Laporan Petani Gurem dan Hutang Musiman.
[5] FAO. (2021). Agroecology for Sustainable Food Systems.
[6] Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Catatan Konflik Agraria Nasional 2022.

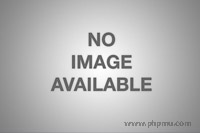 PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN
PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARAN