Catatan Dayak Voices; Sebuah Pengalaman di Indigenous Celebration Bali
Klik Untuk Lebih Jelas : Catatan Dayak Voices; Sebuah Pengalaman di Indigenous Celebration Bali
Klik Untuk Lebih Jelas : Catatan Dayak Voices; Sebuah Pengalaman di Indigenous Celebration Bali
Klik Untuk Lebih Jelas : Catatan Dayak Voices; Sebuah Pengalaman di Indigenous Celebration Bali
Klik Untuk Lebih Jelas : Catatan Dayak Voices; Sebuah Pengalaman di Indigenous Celebration Bali
Semerbak bau bunga kamboja menyambut kedatangan kami sore itu di Bandara Ngurah Rai Bali, selepas perjalanan panjang dari Palangka Raya hingga tiba di pulau Dewata ini. Mata saya pun masih beradaptasi dengan pemandangan sekitar, dimana beberapa patung ukiran mahakarya indah terpampang di beberapa sudut bagian bandara. Bagi saya, tidak sulit untuk kagum dengan Bali, karena anda bisa melihat ada seni dimana-mana. Bukan hanya pada benda, tetapi juga pada orang-orang ramah yang anda akan temui.
Berhubung perhentian kami bukanlah Denpasar atau pun Kuta, maka kami harus menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam untuk tiba di Ubud dengan menggunakan taxi. Biayanya cukup sesuai dengan jauhnya perjalanan dan sedikit jalur macet yang kami temui. Tetapi juga setimpal dengan beberapa pemandangan khas dan indah Bali yang bisa kita lihat sepintas dari dalam mobil.
Dalam perjalanan, sesekali kami mengobrol dan bercanda dengan supir kami. Beliau juga bercerita kalau dulu pernah datang ke Kalimantan untuk bekerja. Ia sendiri bukan asli Bali, tetapi pendatang juga dari Jawa Timur. Ia bercerita pernah sekitar satu tahun jadi supir pribadi seorang janda yang usianya masih muda di Kalimantan Timur, hingga akhirnya diberhentikan oleh orang tua si nona karena ayah nonanya beranggapan kalau tidak wajar jika anaknya di supiri oleh laki-laki.
“Aneh kan, padahal saya nggak pernah macam-macam. Saya cuma niatnya kerja.” Katanya pada saya.
“Waktu saya pulang kampung, rencananya sebentar, tetapi malah dapat telepon diberhentikan oleh bapaknya ibu itu. Padahal saya kan nggak pernah macam-macam. Saya juga kerja untuk keluarga.” Jelasnya lagi pada saya.
Mendengar kisahnya, saya ikut manggut-manggut mengiyakan dibelakang. Saya setuju dengan statement bapak ini. Memang apa salahnya jadi supir dari seorang janda? Toh ia hanya mengabdi untuk dapat gajih buat dikirim ke keluarganya di kampung. Begitupun dengan nonanya, ia hanya membutuhkan jasa supir. Bukan salahnya kalau kebetulan ia janda, dan supirnya laki-laki. Bukankah kebanyakan supir (pribadi) memang laki-laki? Ah, saya masih agak sedikit bingung dengan pandangan orang-orang umum. Kenapa masih ber-statement negative jika ada janda dengan seorang pria. Memang apa bedanya janda dengan wanita-wanita lainnya?
Meskipun perbincangan santai, tetapi saya mendapat pelajaran dan fakta baru tentang perspektif gender di Indonesia. Ternyata, kita juga belum ‘open minded pake banget-banget’ tentang hak dan kesetaraan gender. Masih ada saja pikiran kolot tentang status seseorang terutama terhadap wanita di masyarakat.
Kemudian, si bapak supir ini juga bercerita kalau dia pernah bekerja sekitar satu minggu di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Selatan.
“Nggak sanggup saya mba. Lebih baik saya pulang.” Ceritanya pada saya.
“Lo, kenapa pak?” Tanya saya balik.
“Kerjanya berat sekali. Saya kira sama dengan kerja berladang di kampung, tahunya lebih berat. Tetapi mungkin kalau orang-orang yang sudah biasa berladang dengan kerja berat, mungkin, sudah biasa. Makanya dia bisa bertahan. Kalau saya nggak sanggup.” Lanjut si Bapak lagi dengan mata sambil fokus ke jalan.
“Semua barang mahal dan air juga susah. Untuk mandi kita pakai air hujan. Kalau untuk makan dan minum juga pakai air hujan, tapi yang di endapkan itu.” Kata si bapak
“Kalau kemarau gimana pak?” Tanya saya balik
“Kata teman saya, yang tempat saya tinggal itu, biasanya mereka harus nyetok air beberapa derigen” jawabnya.
“Pokoknya saya nggak sanggup lah mba.” Katanya lagi.
“Belum lagi kalau panen buah sawit. Saya awalnya berpikir masih bisalah karena kelihatannya mudah saja. Sayakan lihat teman saya. Dia badannya kecil, sementara saya lebih besar lah dari dia. Dia bisa aja “dodos” buahnya, jadi saya pasti bisalah. Masak kalah kan…” katanya.
“Tapi mba, pas saya kerjakan…ya, ampun! Berat sekali ternyata. “Dodos” untuk memanen itu ternyata sulit dan berat, tidak semudah yang dilihat. Belum lagi bawa buah sawitnya itu juga berat mba...” Ceritanya pada saya.
“Pokoknya saya nggak tahanlah mba, jadi saya pikir lebih baik cari kerjaan lain aja. Jadi saya pulang. Itupun nggak ada kendaraan lain. Saya ikut truck tambang supaya bisa turun dari camp itu.”
Saya agak sedikit tertawa jahil mendengar cerita bapak ini. Sebab terdengar sekali dari nada bicaranya betapa putus asanya ia saat itu karena pekerjaan yang tidak sesuai pendapatan dan hilangnya harga diri juga karena dikalahkan masalah tenaga untuk “dodos” oleh temannya, yang walaupun berbadan lebih kecil tetapi punya tenaga yang ternyata lebih besar.
“Jadi, gimana pak? Mau balik lagi ke Kalimantan?” Tanya saya bercanda.
“Ah, nggak lah mba. Saya di Bali saja. Lebih enak jadi supir taxi disini dan bisa kumpul juga dengan keluarga.” Jawab si bapak sambil tersenyum sesekali dengan matanya yang tetap fokus ke jalan.
Setelahnya, saya menghilang sesaat dari obrolan karena tertidur sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA), kami tiba di hotel. Saya hanya sempat merebahkan tubuh sesaat diranjang sambil menunggu antrian untuk mandi. Setelahnya kami langsung pergi ke Agung Rai Museum of Art, tempat diadakannya kegiatan Indigenous Celebration, yang merupakan alasan juga mengapa kami jauh-jauh dari Kalimantan Tengah sampai ke sini, untuk mengikuti malam pembukaan.
Banyak sekali masyarakat adat dari berbagai daerah (Indonesia) dan Negara yang datang kesini. Beberapa media menuliskan ada kurang lebih 200 masyarakat adat yang berpartisipasi. Dan, tak kalah banyak pula para “bule” yang antusias datang menghadiri acara ini. Tidak mengherankan memang, apalagi karena acara ini digelar di Ubud, Bali.
Seperti ekspektasi kami, acara pembukaan ini berlangsung meriah. Meskipun kami tidak bisa mengikutinya dari awal, karena baru saja tiba pada malam hari, tetapi kami betah mengikuti acaranya sampai akhir malam itu. Selesai acara, kami kembali ke hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk sharing cerita dan pengalaman sebagai pelaku media dan film pada keesokkan harinya di sesi Indigenous Film Making Workshop.
Keesokkan harinya, 11 Mei 2018, seperti yang telah dijadwalkan oleh pihak penyelenggara, Dayak Voices diberikan kesempatan untuk sharing di satu sesi bersama teman-teman lain; Papuan Voices dan Minahasa. Pada sesi ini, kami memang lebih bercerita tentang apa yang kami lakukan, bukan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat film, teknik , alat-alat ataupun tetek bengek lain dalam pembuatan film. Sebab, kami percaya bahwa film itu tentang seni dan rasa. Setiap orang punya caranya sendiri untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi, tujuan kami adalah saling berbagi cerita ataupun pengalaman, dan juga encouraging satu sama lain.
“Mengajarkan tentang film itu tidak akan cukup hanya dalam satu atau dua jam saja. Workshop dalam waktu satu minggu pun terkadang tidak cukup. Oleh sebab itu, hari ini kami akan lebih berbagi pengalaman tentang apa yang dilakukan dan bagaimana. Sebab, kami, masyarakat adat tidak selalu memiliki alat-alat yang canggih untuk membuat film, tetapi kami menggunakan apa yang ada pada kami, seperti smartphone.” Jelas Kalfein dari Minahasa sebagai pembuka pada sesi ini.
Dan, benar seperti apa yang pria berbadan tegap dengan sorban warna merah bermotif Minahasa ini sampaikan. Kami semua berbagi pengalaman dan struggle kami di lapangan dan prosesnya. Misalnya saja seperti apa yang kita hadapi di Kalimantan Tengah. Isu-isu lingkungan lebih banyak menjadi fokus media dan kampanye dalam gerakkan Dayak Voices. Begitupuan dengan Papua, seperti yang disampaikan Wenda sebagai perwakilan dari Papaun Voices. Isu tentang HAM lah yang menjadi fokus pada film-film yang dibuat oleh gerakan untuk mendukung dan membela kerja dan hak masyarakar adat yang tertindas. Intinya, setiap gerakan, kerja, dan karya yang kami hasilkan selalu berasal, bersama dan untuk masyarakat adat itu sendiri.
Meskipun sebelumnya sempat mengalami beberapa masalah teknis, tetapi akhirnya kami bisa memutarkan beberapa film atau pun video hasil karya kami kepada peserta workshop. Dan respon yang kami dapatkan cukup baik.
“Saya ingin belajar membuat film tentang Indonesia. Saya ingin mengenal masyarakat adat kita. Kalau saya datang ke daerah teman-teman untuk hal ini, apakah saya di terima?” Tanya Marko kepada kami, salah satu film maker dan peserta workshop juga yang datang dari Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini sampai hari terakhir.
Tentu saja pertanyaan Marko kami jawab dengan anggukan dan saran-saran lain, yang intinya menyatakan bahwa tentu saja masyarakat adat akan terbuka tentang hal ini, selama tujuannya baik dan melibatkan mereka. Sebab seperti apa yang Dayak Voices juga percayai bahwa,
“Masyarakat adat bukanlah object, tetapi juga subject yang harus dilibatkan.”
Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam suatu gerakan maupun karya, sebenarnya, merupakan hal yang paling fundamental untuk dan agar dilakukan. Sebab, bagaimana mungkin kita memperjuangkan hak, tetapi kita tidak tahu siapa yang kita perjuangakan? Serta, bagaimana mungkin pula kita katakan mengenal masyarakat adat tetapi kita tidak hidup bersama-sama dengan mereka?
Hari itu kami senang bisa saling berbagi kisah dan pengalaman serta bersolidaritas bersama rekan-rekan dari daerah lain. Tidak hanya berbicara di depan, tetapi juga mendapatkan teman-teman baru seperjuangan.
Namun, tentu saja kegiatan tidak hanya berhenti sampai pada hari itu. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11-13 Mei 2018, dan tetap berlokasi di Agung Rai Museum of Art (ARMA) Ubud, Bali. Sementara siang hari sejak pukul 13.00 – 17.00 WITA diisi dengan berbagai macam workshop, dan malam harinya penampilan dari Indigenous people artists.
Ranu Welum sebagai organizer acara bersama jaringannya yang lain bisa dibilang sukses dalam perhelatan kegiatan ini. Tidak hanya berhasil mengangkat citra masyarakat adat, tetapi juga membawa angin segar bagi masyarakat adat itu sendiri untuk tetap semangat menjaga dan memperjuangkan kearifan lokal, budaya dan adat mereka. Sebab sebagai masyarakat adat mereka masih dihargai dan akan selalu dihargai. Namun tentu saja, harapan juga kami selipkan pada kegiatan ini agar semoga kegiatan ini tidak hanya akan berakhir sebagai euphoria saja, tetapi juga bisa menjadi permulaan untuk gerakan kepada eksistensi masyarakat adat yang lebih besar. Pinar.

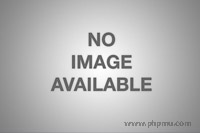 Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini
Pandangan Masyarakat Dayak tentang Alam dan Dinamikanya Hingga Kini